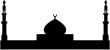|
Atsariyah
Atsariyah (bahasa Arab: الأثرية, translit. al-aṡariyyah [al ʔaθaˈrij.jaɦ]), juga disebut sebagai mazhab akidah tradisionalis atau teologi skripturalis, adalah salah satu mazhab akidah utama Islam Sunni.[a] Mazhab akidah ini muncul pada akhir abad ke-8 M dari para ulama Ahli Hadis, sebuah gerakan keagamaan Islam yang menolak doktrin teologis Islam rasionalistik (kalām) serta mendukung pemaknaan tekstual yang ketat dalam hal menafsirkan Al-Qur'an dan hadis.[1][2] Namanya berasal dari kata aṡar yang berarti "tradisional".[1] Penganutnya dikenal sebagai "Ahli Atsar", "Ahli Hadis", dll.[3][4][5] Penganut Atsariyah berkeyakinan bahwa pemaknaan literal dari Al-Qur'an dan hadis merupakan satu-satunya otoritas yang sah dalam memakanai akidah dan fikih;[1] serta tidak boleh menggunakan perdebatan rasional, bahkan jika untuk memverifikasi kebenaran.[6] Atsariyah tidak setuju dengan penafsiran majasi mengenai deskripsi antropomorfis dan sifat-sifat Allah (maksudnya: mentakwil) serta tidak mengkonseptualisasikan makna Al-Qur'an secara rasional[7] karena mereka meyakini bahwa realitas mereka harus diserahkan kepada Allah saja (tafwidh).[6] Intinya, mereka menegaskan bahwa pemaknaan literal Al-Qur'an dan hadis harus diterima tanpa "bagaimana caranya memaknainya" (yaitu bi-la kaifa). Mazhab akidah muncul di kalangan ulama hadits yang akhirnya bergabung menjadi gerakan yang disebut Ahli Hadis di bawah kepemimpinan Ahmad bin Hanbal (780–855).[8][b] Dalam masalah iman, mereka melawan pemahaman Muktazilah serta akidah Islam lainnya serta dan mengutuk banyak sekali doktrin-doktrin mereka serta mengedepankan metode rasionalistik secara ekstrem.[8] Pada abad ke-10, al-Asy'ari dan al-Maturidi menemukan jalan tengah antara ilmu kalam Muktazilah dan ilmu atsar Hambali, menggunakan metode ilmu kalam yang diperjuangkan oleh Muktazilah untuk mempertahankan sebagian besar ajaran doktrin Atsariyah.[9] Meski ulama Hambali yang menolak sintesis itu berjumlah sedikit, pendekatan berbasis narasi dan emosional terhadap iman memiliki pengaruh besar di kalangan penduduk perkotaan yang tinggal di beberapa wilayah dunia Muslim, khususnya di Baghdad era Abbasiyah.[10] Asy'ariyah dan Māturīdiyah sering dianggap sebagai mazhab akidah "ortodoks" Sunni, tetapi akidah Atsariyah berkembang pesat bersama keduanya sebagai tandingan akidah Sunni ortodoks.[11] Di era modern, Atsariyah memiliki dampak tidak proporsional pada akidah, dan telah diadopsi oleh aliran Wahhabi dan Salafi tradisionalis lainnya, dan menembus batas-batas mazhab fikih Hanbali.[12] TerminologiBeberapa istilah digunakan untuk menyebut teologi Atsariyah. Penggunaannya cenderung tidak konsisten, dan telah banyak dikritik. Istilah "teologi tradisionalis" diturunkan dari kata "tradisi" untuk memaknai istilah bahasa Arab ḥadiṡ.[1][13] Peristilahan ini muncul dalam beberapa kitab rujukan.[1][14] Istilah ini dikritik oleh Marshall Hodgson (yang lebih suka menggunakan istilah "masyarakat hadis" (Hadith folk)) [15] karena berpotensi membingungkan antara makna teknis dan makna umum dari kata "tradisi".[15] Oliver Leaman juga mengingatkan agar tidak salah memaknai istilah "tradisionalis" dan "rasionalis", bahwa yang pertama menyukai irasionalitas atau bahwa yang terakhir tidak menggunakan hadis.[16] Beberapa penulis menolak penggunaan istilah ini sebagai cap untuk para ulama dan lebih memilih untuk membahas kecenderungan "tradisionalis" dan "rasionalis".[17] Racha el Omari sudah menerapkan sebutan mazhab akidah tradisionalis untuk menyebut Asy'ariyah dan Māturīdiyah.[18] Atsariyah (dari kata bahasa Arab aṡar, berarti "dampak" atau "sisa") adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut teologi tradisionalis.[19] Istilah "Tradisionisme" juga telah dipakai dalam pemaknaan yang sama,[20] meski Binyamin Abrahamov mencanangkan istilah "tradisionis" untuk para ulama hadis, sehingga berbeda dengan "tradisionalis" sebagai mazhab teologis.[1] Istilah "Ahli Hadis " digunakan oleh beberapa penulis dalam pemaknaan yang sama dengan Atsariyah,[21] sementara yang lain membatasinya pada tahap awal gerakan ini,[22] atau menggunakannya dalam arti yang lebih luas untuk menunjukkan minat khusus terhadap literatur hadis.[23] Karena sebagian besar ulama di mazhab fikih Hambali menganut mazhab akidah Atsariyah, banyak sumber yang menyebutnya sebagai "mazhab akidah Hambali", meski pakar studi Islam Barat menyatakan bahwa Atsariyah dan Hambali bukanlah sinonim, karena ada ulama mazhab tersebut yang menolak mazhab akidah ini.[24] Namun, yang lain juga mencatat bahwa beberapa ulama Syafiʽi juga termasuk dalam mazhab akidah ini, sedangkan ada ulama Hambali yang mengadopsi mazhab akidah yang lebih rasionalis.[25] Selain itu, bentuk-bentuk tradisionalisme ekstrem tidak hanya dijumpai di mazhab Hambali, tetapi juga Maliki, Syafi'i, dan Hanafi.[26] Beberapa penulis menyebut akidah tradsionalisme sebagai "Salafiyah klasik" (dari salaf, yang berarti "orang-orang (saleh) yang terdahulu").[27] Henri Lauzière berpendapat bahwa, meski keyakinan mayoritas Hambali kadang-kadang diidentifikasi sebagai "Salafi" dalam sumber-sumber klasik, menggunakan kata-kata dalam memaknai konteks ini dianggap anakronistik.[28] Sejarah
Asal usulSejarawan dan fakih Muslim beranggapan bahwa sahabat Nabi Islam Muhammad, Zubair bin Awwam adalah salah satu ulama tradisionalis dan tekstualis paling awal yang memengaruhi skolastisisme Atsariyah.[29] Pendekatan proto-tekstualis Zubair[30] memengaruhi ulama Ahli Hadis. Hal ini ditandai dengan pendekatan mereka terhadap kepatuhan literal terhadap teks Al-Qur'an dan hadis, sementara sebagian besar menolak Qiyas (analogi) yang diajukan oleh Ahlur-Ra'y (ahli logika).[29] Pandangan ketat yang diungkapkan oleh az-Zubair mengenai penafsiran Al-Qur'an muncul dalam biografi besarnya yang disusun oleh para ulama. Termasuk nasihat Zubair kepada salah satu anaknya untuk tidak pernah memperdebatkan pemaknaan teks Al-Qur'an dengan akal. Menurut Zubair, tafsir Al-Qur'an harus disempurnakan dengan pemahaman hadis dan sunnah. Pandangan anti-rasionalistis, tradisionalistis, dan berorientasi hadis seperti itu juga dimiliki oleh banyak ulama berpengaruh dalam sejarah yang mencapai peringkat mujtahid mutlak seperti ulama Syafiʽi Ibnu Katsir, ulama Hanbali Ibnu Taimiyah,[31][32] Ibnu Hazm, al-Bukhari,[33] dan juga ulama dari mazhab Jariri dan Zhahiri .[34] Sahabat lainnya yang mendukung pemahaman atsar adalah 'Abdullah ibn Umar. Saat ditanya tentang sekelompok murid Tabiin tentang pandangannya tentang Qadariyah, Ibnu 'Umar menjawab secara lembut sebagai kelompok takfir (keluar dari Islam) karena menolak rukun iman ke-6, qadar (takdir). Dia juga mengutuk penggunaan qiyas mereka. Menurut ulama kontemporer, alasan cap Qadariyah oleh Ibnu Umar tersebut kesamaan doktrin mereka dengan Zoroastrianisme dan Maniisme karena kosmologi dualistiknya masing-masing, yang sejalan dengan salah satu riwayat yang berbunyi: “Qadariyah adalah Majusinya umat ini”. PembentukanAtsariyah muncul sebagai mazhab akidah yang berbeda menjelang akhir abad ke-8 M di antara para ulama hadis yang menganggap Al-Qur'an dan hadis shahih sebagai satu-satunya sumber hukum yang dapat diterima dalam masalah hukum dan keyakinan.[8] Di samping Malik bin Anas, ulama Ibnu Idris asy-Syafi'i secara luas dianggap sebagai salah satu pemimpin paling awal dari mazhab Atsariyah. Dalam perdebatan antara kelompok kalam dan atsar, asy-Syafi'i berhasil membuktikan keunggulan hadis terhadap hukum lainnya seperti dalil akal, tradisi lokal, adat istiadat, ra'y, dll. sebagai sumber akidah, ilmu pengetahuan, dan tafsir Al-Qur'an.[35] Dari mazhab ini muncul gerakan atsariyah yang cukup kuat melawan Ahlur-Ra'y dan berbagai manifestasinya.[36][37] Doktrin para ulama mazhab Syafi'i kelak dilahirkan kembali dalam risalah ulama Hambali kemudian.[38] Semula ulama-ulama yang ada dalam lingkaran studi ini minoritas, tetapi sejak awal abad ke-9 M, mereka bersatu menjadi gerakan skolastik tradisionalis baru, yang dikenal sebagai Ahli Hadis, di bawah pimpinan Ahmad bin Hanbal.[8][39] Pemimpin ulama kubu tradisionalis yang lainnya pada zaman ini adalah Dawud bin Khalaf, pendiri mazhab Zhahiri. Di bawah kepemimpinan dua ulama ini, kubu Atsariyah memperoleh kekuasaan.[40] Dalam masalah hukum, kaum tradisionalis ini mengkritik penggunaan pendapat pribadi (ra'y) yang umum di antara para fakih Hanafi di Irak serta tradisi lokal yang hidup oleh para fakih Maliki di Madinah.[8] Mereka menekankan penggunaan nash Kitab Suci, mencela peran akal manusia dan juga menolak metode fikih yang tidak berdasarkan nash kitab suci secara literal. Tidak seperti tradisionalis arus utama, Dawud melangkah lebih jauh dengan menyatakan semua bentuk Qiyas sama sekali tidak valid.[8][40] Dalam masalah akidah, kaum tradisionalis terus melawan Muktazilah dan mazhab teologis lainnya, serta mengutuk banyak pokok-pokok pikiran doktrin mereka serta metode rasionalistik yang mereka gunakan dalam mempertahankannya.[8] Kelompok ini cenderung menghindari perlindungan hak-hak mereka oleh negara serta aktivisme sosial.[8] Mereka berusaha mengikuti perintah "mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran " dengan menyebarkan asketisme dan melakukan pemusnahan botol anggur, alat musik, dan papan catur.[8] Pada tahun 833, khalifah al-Ma'mun mencoba untuk memaksakan teologi Muktazilah pada semua ulama dan melembagakan sebuah mihnah yang mewajibkan ulama untuk menerima doktrin Muktazilah bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, yang secara implisit membuat Al-Qur'an tunduk pada tafsir para khalifah dan ulama.[41] Ibnu Hanbal berupaya memimpin kaum tradisionalis melawan kebijakan ini, menegaskan di bawah penghukuman oleh penguasa bahwa Al-Qur'an tidak diciptakan dan karenanya sama abadinya dengan Tuhan.[42] Meskipun Muktazilah bertahan sebagai doktrin resmi negara sampai 851, upaya pemaksaannya hanya mempolitisasi dan memperkeruh kontroversi teologis.[43] Gagalnya kampanye Mihnah menjadi tanda kekalahan telakkaum Mu'tazilah dan kemenangan doktrin tradisionalis yang teraniaya, yang didukung rakyat. Selain kecaman terhadap doktrin Al-Qur'an sebagai makhluk; akal ditentang dalam hal penafsiran agama karena harus mengikuti nash Wahyu dalam paradigma hermeneutis Sunni.[44] Munculnya ilmu kalamPada dua abad berikutnya, muncul kompromi yang luas dalam fikih dan akidah Islam Sunni. Dalam fikih, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali semuanya berangsur-angsur menerima kepercayaan tradisionalis pada Al-Qur'an dan hadis serta penggunaan penalaran berarah dalam bentuk qiyas.[45] Dalam akidah, al-Asy'ari (874-936) menemukan jalan tengah antara ahli kalam Muktazilah dan ahli atsar Hambali, dengan menggunakan metode ilmu kalam yang pernah diajukan Muktazilah untuk mempertahankan sebagian besar doktrin Atsariyah.[9] Selain itu, pertandingan ilmu kalam dan ilmu atsar muncul dari karya al-Māturīdī (w. 944), dan salah satu dari dua mazhab akidah ini diterima oleh kelompok Sunni, kecuali sebagian besar ulama Hambali dan sebagian kecil ulama Maliki dan Syafi'i, yang bersikeras menolak ilmu kalam, meskipun mereka sendiri juga menggunakan argumen rasionalistis, bahkan saat mereka mengeklaim mengandalkan teks literal dari kitab suci Islam.[9] Tanggapan tradisionalis terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah dan sebaliknyaMeski ulama yang menolak sintesis mazhab akidah Asy'ariyah (Asya'irah) dan Maturidiyah terhitung minoritas, pendekatan iman mereka yang berbasis narasi dan emosional memberi pengaruh di kalangan penduduk kota di beberapa belahan Dunia Muslim, khususnya di Baghdad zaman Abbasiyah.[10][46] Popularitasnya dalam memanifestasikan dirinya terjadi beberapa kali dari akhir abad ke-9 hingga ke-11, ketika masyarakat banyak meneriaki para pendakwah yang secara terbuka menguraikan teologi rasionalistis.[46] Setelah khalifah al-Mutawakkil menangguhkan inkuisisi kelompok rasionalis, khalifah Abbasiyah bersatu dengan kaum tradisionalis untuk menopang dukungan rakyat.[46] Pada awal abad ke-11, khalifah al-Qadir memproklamasikan pencegahan penyebaran mazhab akidah rasionalistis secara publik.[47] Pada gilirannya, wazir Seljuk, Nizam al-Mulk pada akhir abad ke-11 mendorong para teolog Asy'ariyah untuk mengimbangi tradisionalisme khalifah, mengundang beberapa dari mereka untuk berdakwah di Baghdad selama bertahun-tahun. Salah satu kejadian tersebut menyebabkan kerusuhan selama lima bulan di kota tersebut pada tahun 1077.[47] Era modern dan kontemporerMeski Asy'ariyah dan Maturidiyah sering disebut sebagai "Sunni Ortodoks", mazhab akidah Atsariyah semakin berkembang pesat bersamanya, serta mengeklaim sebagai Sunni Ortodoks pula.[11] Di era modern ini memiliki dampak yang tidak proporsional pada teologi Islam, yang telah digagas oleh aliran Wahhabi dan Salafi tradisionalis lainnya dan menyebar melewati batas-batas mazhab fikih Hambali.[12] Karya-karya ulama Sunni Yaman abad ke-19 Muhammad Asy-Syaukani (w. 1839 M/1255 H) telah memberikan kontribusi besar bagi kebangkitan Atsariyah di era kontemporer.[48][49] Atsariyah juga memberikan pengaruh signifikan dalam mazhab fikih Hanafi, seperti syarh ulama Hanafi Ibnu Abi al-Izz tentang risalah akidah ath-Thahawi Al-Aqidah at-Thahawiyyah. Risalah ini kemudian menjadi populer di kalangan penganut gerakan Salafiyah kemudian, yang menganggapnya sebagai representasi sebenarnya dari akidah Hanafi yang lepas dari pengaruh Māturīdīyah. Banyak ulama Salafi modern telah menulis tahqiq dan tafsir terhadap syarh seperti Syekh 'Abdul-'Aziz bin Abdullah Bin Baz, Muhammad Nashiruddin al-Albani, dan Shalih bin Fauzan al-Fauzan, dan menjadi kitab pegangan di Universitas Islam Madinah.[50] KeyakinanAsas doktrin Atsariyah adalah:
Terhadap taklidSikap Atsariyah terhadap prinsip agama membuat mereka membedakan dua istilah yang hampir mirip: Taklid dan Ittiba. Taklid, yang merupakan kepatuhan kepada ulama tanpa dalil kitab suci (ra'y), dikutuk keras. Selain itu, Atsariyah memahami Ittiba sebagai mengikuti ajaran kenabian dengan menggunakan bukti kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Banyak penganut Atsariyah seperti Ahmad bin Hanbal (wafat 855), seorang ulama besar yang mengartikulasikan Ijtihad dan menolak Taqlid, menggunakan dalil nash Al-Qur'an dan sunnah tetapi juga dalam beberapa kasus, dalil akal.[1][52] Penentangan kelompok Atsariyah terhadap taklid telah mencapai puncaknya dalam tulisan-tulisan ulama abad ke-8/14, Ibnu Taimiyyah (w. 1328 M/728 H) dan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah (w. 1350 M/751 H). Menurut Ibnu Taimiyyah, setiap orang yang menyimpang dari nash yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis serta mengedepankan pendapat individu termasuk orang-orang yang kembali ke zaman Jahiliah dan layak dihukum.[53] Dalam salah satu fatwanya yang mengecam keras taklid buta, Ibnu Taimiyyah menyatakan:
Penggunaan akalSelain mematuhi secara ketat Al-Qur'an, hadis, sunnah, dan ijmak, serta ijtihad, Atsariyah tidak sepenuhnya mengabaikan penggunaan akal. Menurut kaum tradisionalis, akal berfungsi sebagai hujjah terhadap wahyu ilahi. Terlepas dari kritik tradisionalis terhadap teologi rasionalis, akal memainkan peranan penting dalam teologi Atsariyah.[55] Menurut ulama Hambali dan teolog Sunni Ibnu Taimiyyah (w. 1328), keputusan untuk menyimpang dari tradisi dan mengadopsi pendekatan rasionalis menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyyah menganjurkan kembali doktrin teologis Atsariyah, yang mengedepankan kembali ke tradisi awal.[56] Menyimpulkan pandangan kaum tradisionalis terhadap argumentasi rasional, Ibnu Taimiyyah menulis:
Terhadap Al-Qur'anTeolog Atsariyah meyakini Al-Qur'an bukanlah makhluk.[57][58] Ahmad bin Hanbal (wafat 855) berkata, "Al-Qur'an adalah Kalamullah, yang Dia ungkapkan; tidak diciptakan. Yang mengklaim sebaliknya adalah kelompok Jahmiyah, yang merupakan orang kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an adalah Kalamullah, dan berhenti tanpa menambahkan 'yang tidak Dia ciptakan,' maka ucapannya lebih buruk daripada yang pertama".[59] Terhadap ilmu kalamMenurut penganut Atsariyah, nalar manusia sangat terbatas, dan bukti-bukti rasional tidak dapat dipercaya atau diandalkan untuk persoalan keyakinan, sehingga ilmu kalam dianggap bid'ah.[6] Bukti-bukti yang rasional, kecuali termuat jelas dalam Al-Qur'an, dianggap tidak ada dan sama sekali tidak sah.[60] Akan tetapi, hal itu tidak mesti terjadi karena banyak Atsariyah mendalami ilmu kalam, terlepas dari apakah mereka memaknainya demikian atau tidak.[61] Contoh Atsariyah yang menulis buku yang menentang penggunaan ilmu kalam[62] dan akal misalnya ulama Sufi Hambali Khwaja Abdullah Ansari dan fakih Hambali Ibnu Qudamah.[63] Ibnu Qudamah mencela kalam sebagai sebuah kesesatan. Ia menganggap para ulamanya, mutakallimūn, sebagai ahli bid'ah yang telah mengkhianati dan menyimpang dari salafusshalih. Ia menulis, "Ulama akidah ini sangat dicela di dunia, serta disiksa di akhirat. Tidak ada di antara mereka yang akan selamat, juga tidak akan mengikuti jalan yang benar...".[64] Sifat-sifat Allah
Atsariyah mengakui keberadaan sifat-sifat Allah dan menganggap seluruhnya kekal dan setara. Mereka menerima ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagaimana mestinya tanpa melakukan analisis lanjut atau elaborasi rasional [65] Menurut Atsariyah, pemaknaan yang sesungguhnya dari sifat-sifat Allah harus diserahkan hanya kepada Allah (tafwidh).[6] Dalam metode ini, orang harus berpegang teguh pada nash Al-Qur'an dan meyakini bahwa itu adalah kebenaran, tanpa memaknainya sebagai sebuah majas.[66] Dalam sebuah riwayat, Ahmad bin Hanbal menyatakan: "Sifat-sifat-Nya berasal dari-Nya dan milik-Nya sendiri, kami tidak melampaui batas-batas Al-Qur'an dan perbuatan para Nabi dan para sahabatnya; kami juga tidak mengetahui bagaimana pemaknaannya, kecuali dengan pengakuan dari Rasul dan penegasan Al-Qur'an".[6] Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan: “Kita tidak perlu mengetahui makna yang Allah maksudkan dengan sifat-sifat-Nya; tidak ada tindakan yang dimaksudkan oleh sifat-sifat itu, juga tidak ada kewajiban yang melekat padanya. Dimungkinkan untuk yakin tanpa memaknainya lebih lanjut dengan akal".[67] Antropomorfisme (Tasybih) sering dituduhkan kepada penganut Atsariyah oleh para pengkritiknya,[7] termasuk ulama Hambali, Ibnul-Jauzi. Dalam beberapa kasus, ulama Atsariyah menganut pandangan tasybih yang ekstrem,[7] tetapi tidak mewakili teologi Atsariyah secara keseluruhan.[6] Tentang imanAtsariyah berkeyakinan bahwa iman dapat meningkat dan menurun sehubungan dengan pelaksanaan ritual dan kewajiban, seperti salat lima waktu.[68][69] Iman akan bersemayam dalam hati, dalam ucapan lisan, serta dalam perbuatan anggota badan.[59] Pembagian TauhidIbnu Taimiyyah diyakini sebagai orang pertama yang memperkenalkan pembagian tauhid.[70][71] Ulama mazhab akidah Atsariyah mendukung pembagian tauhid menjadi tiga kategori:
KritikSeorang ulama Asy'ariyah abad ke-16, Ibnu Hajar al-Haytami mengkritik mazhab akidah Atsariyah yang dikaitkan dengan doktrin Ibnu Taimiyyah.[72] Lihat pulaCatatan kaki
Referensi
Daftar pustaka
|